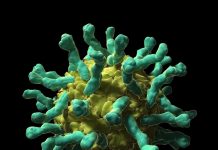S
eperti tulisan saya di masa lalu, bahwa pengelolaan uang negara tak ubahnya seperti pengelolaan uang RT. Para warga beriuran dalam jumlah tertentu yang cukup untuk membiayai keperluan pemeliharaan lingkungan. Ada kalanya mungkin iuran berlebih, tetapi mungkin juga ada kalanya iurannya kurang. Misal, ketika ada anggota yang menunggak atau ada kebutuhan khusus membantu warga yang dalam kondisi sulit. Dalam kondisi ini, bisa saja ketua RT atau beberapa warga menalangi terlebih dahulu kekurangannya. Kelak, ketika warga yang menunggak sudah mampu membayar, pinjamannya dilunasi.
Demikian juga keuangan negara, yang sebagian besar dibiayai iuran warga negara dalam bentuk pajak dan pungutan lainnya. Ada kalanya iuran warga negara tidak cukup membiayai belanja negara. Ini biasa terjadi ketika kondisi ekonomi sulit, iuran pajak tidak cukup karena pendapatan warga negara juga berkurang. Sementara belanja negara belum tentu berkurang banyak, bahkan bisa jadi bertambah untuk membantu perekonomian warga negara yang kesulitan.
Untuk mengatasi defisit keuangan ini, pemerintah akan meminjam dulu pada warga yang memiliki uang yang lebih. Kelak, ketika perekonomian membaik, pendapatan warga meningkat dan demikian juga jumlah pajak yang dibayarkan, pemerintah akan melunasi utang tadi.
Disiplin Fiskal
 Seperti halnya kita mengatur keuangan personal, perlu keberhati-hatian dan disiplin yang tinggi dalam mengelola keuangan negara, biasa dikenal dengan kebijakan fiskal, strategi pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Seperti yang kita ketahui, jumlah utang yang diluar kemampuan, atau besar pasak daripada tiang, seringkali berujung pada krisis, merontokkan tiang perekonomian tersebut.
Seperti halnya kita mengatur keuangan personal, perlu keberhati-hatian dan disiplin yang tinggi dalam mengelola keuangan negara, biasa dikenal dengan kebijakan fiskal, strategi pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Seperti yang kita ketahui, jumlah utang yang diluar kemampuan, atau besar pasak daripada tiang, seringkali berujung pada krisis, merontokkan tiang perekonomian tersebut.
Selalu ada godaan untuk berutang agar dapat menikmati dan memiliki banyak hal hari ini, sementara beban pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang. Godaan ini lebih besar dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk utang personal setidak-tidaknya ada deterrence karena, seperti kata orang-orang, utang akan mengejar kita hingga ke liang kubur. Sementara utang negara, nikmat utang dapat dinikmati langsung sekarang, namun pembayarannya bisa jadi urusan pemerintahan atau generasi nanti.
Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, disiplin dalam mengelola keuangan negara, disiplin fiskal, adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Di sebagian besar negara, termasuk Indonesia, salah satu pilar kedisiplinan ini adalah dengan menjaga tingkat hutang. Hutang berasal dari akumulasi defisit anggaran setiap tahunnya. Oleh karena itu defisit anggaran juga diatur.
Menurut UU defisit anggaran setiap tahunnya tidak boleh melebihi 3% dari PDB atau nilai aktivitas ekonomi. Sementara, maksimal total hutang yang dimiliki pemerintah tidak boleh melebih 60% dari nilai PDB.
Disiplin fiskal ini adalah salah fondasi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, disiplin fiskal terjaga sangat baik dalam 15-20 tahun terakhir, dan menjadi salah pilar kekuatan perekonomian Indonesia yang memberikan kenyamanan pada pelaku ekonomi dan investor.
Independensi Bank Sentral
Satu fondasi dasar lagi yang tak kalah pentingnya adalah independensi pengelolaan moneter, yaitu pengelolaan jumlah uang yang beredar, serta harganya (suku bunga). Tujuan dasar dari pengelolaan moneter adalah menjaga jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan aktivitas ekonomi, serta tidak mengakibatkan inflasi yang berlebihan.
 Independensi bagi bank sentral, sebagai otoritas moneter, adalah prasyarat utama dalam menerapkan kebijakan moneter yang efektif. Kebijakan dan keputusan dalam mengelola kondisi moneter sepenuhnya diputuskan oleh bank sentral tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah. Sejarah menunjukkan, krisis ekonomi sering terjadi di berbagai penjuru dunia, karena pemerintah atau politikus ingin memanfaatkan bank sentral untuk kepentingan jangka pendek.
Independensi bagi bank sentral, sebagai otoritas moneter, adalah prasyarat utama dalam menerapkan kebijakan moneter yang efektif. Kebijakan dan keputusan dalam mengelola kondisi moneter sepenuhnya diputuskan oleh bank sentral tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah. Sejarah menunjukkan, krisis ekonomi sering terjadi di berbagai penjuru dunia, karena pemerintah atau politikus ingin memanfaatkan bank sentral untuk kepentingan jangka pendek.
Biasanya dalam bentuk intervensi agar menyediakan uang beredar dalam jumlah besar dan/atau dalam harga yang murah (suku bunga rendah) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka pendek, atau kepentingan vested interest. Seringkali juga intervensi langsung untuk membiayai kebijakan fiskal. Namun, hal ini dapat menghasilkan ketidakstabilan, bahkan seringkali berujung pada krisis ekonomi. Biasanya dalam bentuk anjloknya nilai mata uang, baik terhadap barang (inflasi) maupun terhadap mata uang asing (depresiasi).
Independensi bank sentral ini lebih krusial bagi negara berkembang, yang biasanya kelembagaan, tata kelola, serta penegakan hukum relatif lemah. Sehingga, pelaku ekonomi dan investor membutuhkan keyakinan ekstra sebelum benar-benar dapat mempercayai integritas bank sentral.
Krisis ekonomi dalam bentuk hiperinflasi seperti yang terjadi di Zimbabwe dan Venezuela adalah contoh ekstrim pengelolaan fiskal yang tidak disiplin dan populis. Pemerintah berkuasa kemudian mencoba mencari “solusi” dengan merenggut independensi bank sentral dan memaksanya untuk membiayai defisit fiskal tadi, dengan mencetak uang secara tidak terkendali.
Indonesia, terutama dalam konteks negara berkembang, sangat diapresiasi dalam membangun kredibilitas bank sentral yang independen. Independensi Bank Indonesia, sebagai bank sentral di Indonesia, dijamin oleh UU.
Pelanggaran/Pelonggaran Disiplin Fiskal
Batas-batas yang diterapkan untuk menjamin kedisiplinan fiskal, dalam rangka meraih pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, bisa diperdebatkan. Tetapi, limit 3% defisit dan 60% total hutang relatif terhadap PDB, merupakan limit yang diterima luas, dan mengacu pada kebijakan serupa di Uni Eropa.
Akan tetapi, ketika kondisi dalam kesulitan yang lebih besar dari biasanya, ketika perekonomian mengalami penurunan aktivitas yang luar biasa, apakah kita dapat lebih fleksibel dan menerobos batas limit 3% dan 60% tadi?
 Seperti yang saat ini terjadi di Indonesia. Krisis pandemi covid-19 membawa penurunan tajam pada aktivitas ekonomi, sepertinya yang terburuk dalam 20 tahun terakhir. Salah satu akibatnya pendapatan pemerintah berkurang, karena aktivitas ekonomi yang turun juga akan menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan warga. Di sisi lain, pemerintah bisa jadi malah harus mengeluarkan biaya tambahan, baik untuk mengatasi isu kesehatan atau pun mendorong perputaran ekonomi. Artinya akan ada defisit yang lebih besar dari biasanya.
Seperti yang saat ini terjadi di Indonesia. Krisis pandemi covid-19 membawa penurunan tajam pada aktivitas ekonomi, sepertinya yang terburuk dalam 20 tahun terakhir. Salah satu akibatnya pendapatan pemerintah berkurang, karena aktivitas ekonomi yang turun juga akan menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan warga. Di sisi lain, pemerintah bisa jadi malah harus mengeluarkan biaya tambahan, baik untuk mengatasi isu kesehatan atau pun mendorong perputaran ekonomi. Artinya akan ada defisit yang lebih besar dari biasanya.
Pertanyaannya, bagaimana jika strategi yang optimal menurut pemerintah, menjadikan defisit APBN lebih dari 3% PDB? Secara hukum, ini tidak dapat dilakukan pemerintah, karena akan melanggar UU. Namun, pemerintah berpendapat dalam situasi yang luar biasa ini, pemerintah perlu diberikan kelonggaran khusus. Belanja negara perlu diperkuat, dengan pendapatan yang turun, maka defisit akan melejit lebih dari 3%, yang akan dibiayai dengan berhutang pada warga negara sendiri atau warga asing.
Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun menjaga disiplin fiskal pada defisit 3%, pemerintah dengan dukungan DPR, memutuskan melonggarkan disiplin ini. Dikeluarkan aturan yang merevisi UU tadi, yang memungkinkan sekarang pemerintah untuk berhutang lebih banyak, dengan meniadakan batas maksimal 3%. Dinyatakan, ini hanya bersifat sementara beberapa tahun ke depan, dan limit defisit anggaran kembali “normal” menjadi 3% pada tahun 2023.
Dalam kondisi yang normal, pelaku ekonomi dan investor akan khawatir ketika sebuah negara melanggar disiplin fiskalnya. Namun, walau ada kegamangan pada sebagian investor, sejauh ini pelanggaran atau pelonggaran disiplin fiskal ini relatif dapat diterima. Mengingat juga, pelonggaran disiplin fiskal seolah-olah menjadi “norma” baru dunia yang lebih dapat diterima, dan dilaksanakan oleh banyak negara di situasi sulit ini.
Implementasi Pelonggaran Fiskal Dengan “Mengorbankan” Independensi Bank Sentral
Pelonggaran fiskal melebihi 3%, misalnya menjadi defisit 5% dalam target awal, belum tentu dapat diimplementasikan jika tidak ada pihak yang mau memberikan hutang untuk mendanai defisit yang besar tersebut. Atau kalaupun ada, mereka meminta bayaran bunga yang besar, yang akhirnya percuma karena anggaran tersedot banyak hanya untuk membayar bunga.
 Dengan situasi yang demikian, pemerintah mendekati Bank Indonesia, dan meminta Bank Indonesia untuk meminjamkan uang pada pemerintah Indonesia. Dalam prakteknya, Bank Indonesia akan membeli obligasi yang diterbitkan pemerintah.
Dengan situasi yang demikian, pemerintah mendekati Bank Indonesia, dan meminta Bank Indonesia untuk meminjamkan uang pada pemerintah Indonesia. Dalam prakteknya, Bank Indonesia akan membeli obligasi yang diterbitkan pemerintah.
Tapi bukankah Bank Indonesia sebagai otoritas moneter harus independen? Bahwa kebijakan dan operasional mereka tidak dapat dipengaruhi apalagi diperintah oleh pihak lain? Secara khusus lagi, adalah “haram” bagi bank sentral membiayai anggaran fiskal negara. UU melarang BI untuk memberikan pinjaman ataupun membeli obligasi langsung dari pemerintah.
BI hanya dibolehkan membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder, sesuai mekanisme pasar. Ini dilakukan dalam rangka operasi moneter atas inisiatif BI sendiri, bukan dengan tujuan pembiayaan fiskal atas permintaan atau instruksi dari pemerintah.
Namun, rasionalnya sama dengan yang disampaikan sebelumnya, bahwa kali ini perekonomian dalam kondisi luar biasa, perlu penanganan yang luar biasa. Kali ini, BI akan membeli langsung obligasinya dari pemerintah (private placement), dan sesuai “instruksi” pemerintah, dan dalam rangka membantu kebijakan fiskal, bukan dalam rangka pengelolaan kebijakan moneter.
Agar tidak melanggar UU yang berlaku maka diterbitkan juga aturan untuk merevisi larangan-larangan yang ada dalam UU tersebut.
Independensi Bank Indonesia dan pemisahan kebijakan moneter dan fiskal terpaksa diakhiri dulu. Independensi bank sentral yang, dalam opini saya, bahkan seharusnya lebih sakral daripada batasan defisit anggaran dalam konteks disiplin fiskal.
Bagaimana respon pelaku ekonomi dan investor? Tentu ada kegamangan dan kekhawatiran, walau belum banyak reaksi yang berlebihan di pasar. Namun, ada berbagai pertanyaan atau berbagai skenario “prasangka” muncul di benak investor dan pelaku ekonomi.
 Yang pertama, sejauh mana independensi BI akan digerus oleh pemerintah. Apakah berhenti di sini atau ada kelanjutannya, dan what’s the limit?
Yang pertama, sejauh mana independensi BI akan digerus oleh pemerintah. Apakah berhenti di sini atau ada kelanjutannya, dan what’s the limit?
Yang kedua, apakah ada jaminan pendanaan dari BI untuk anggaran negara tidak berujung pada monetisasi hutang secara permanen. Dalam bahasa lain BI dipaksa untuk literally “cetak uang” membiayai belanja negara, baik secara penuh atau sebagian, secara langsung atau “di belakang layar”.
Namun, ada assurance atau self assurance bahwa peminjaman uang yang dilakukan oleh BI pada pemerintah dilakukan secara transparan dengan mengikuti mekanisme dan pricing yang berlaku di pasar, misal dengan BI menjadi non-competitive bidder. Dan karena ini adalah utang dengan jangka waktu tertentu, pemerintah tentu akan mengembalikan uang tersebut pada BI. Jadi, BI tidak membiayai belanja fiskal negara, tetapi sekedar menalangi.
Yang ketiga, bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan moneter BI sendiri. Setiap pendanaan yang diberikan BI pada pemerintah, yang akan dibelanjakan pemerintah pada sektor riil, akan menambah uang beredar dan teorinya bersifat inflationary. Artinya, kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka mendanai APBN mempengaruhi kebijakan moneter yang seharusnya secara independen diputuskan oleh BI.
Sejauh ini, sepertinya pelaku pasar cenderung percaya bahwa setiap penambahan uang beredar dari aktivitas langsung antara BI dan pemerintah ini akan dikelola oleh BI at the high level. Artinya, jika BI menganggap hal ini mengakibatkan bertambahnya uang beredar dan tekanan terhadap inflasi lebih dari yang ditargetkan BI, maka BI dapat men”sterilisasi” sebagian atau seluruhnya dengan melakukan operasi moneter.
Eskalasi “Indisiplin” Fiskal yang Kian Merenggut Independensi Moneter
Sebagai mantan pelaku pasar yang telah beberapa tahun tidak mengikuti perkembangan ekonomi secara detil dan saksama, saya sebetulnya tidak terlalu nyaman untuk beropini terlalu jauh. Ada pihak-pihak lain yang lebih berkompenten. Namun, sebuah berita yang dibagikan seorang teman beberapa waktu lalu menggugah saya berfikir dan nekad menuliskannya di sini, dengan segala keterbatasan akses informasi dan sisa-sisa ilmu yang ada.
Mengulang pertanyaan pertama saya sebelumnya: sejauh mana independensi BI akan digerus oleh pemerintah? Apakah berhenti di sini atau ada kelanjutannya?
Sayang sekali, ternyata ada kelanjutannya.

“Burden Sharing antara pemerintah dan BI”, itulah berita yang saya baca yang membuat saya takjub. Intinya, pemerintah dan BI “bersepakat” akan berbagi beban dalam mendanai defisit, dalam mendanai sebagian belanja negara.
Awalnya, mungkin ada “kecurigaan” bahwa BI akan membantu mendanai belanja pemerintah di belakang layar. Bahwa BI akan mentransfer surplus, misal dari bunga yang dibayarkan pemerintah, kembali ke pemerintah, melalui mekanisme rekapitalisasi, atau dekapitalisasi dalam situasi ini.
Namun, ternyata pemerintah dan BI tidak perlu diam-diam di belakang layar, mereka mengumumkannya secara blak-blakan. Bahwa, BI akan membantu pemerintah mendanai anggaran.
Prosesnya juga tidak mengikut mekanisme pasar, tetapi dengan memberikan diskon terhadap suku bunga yang harus dibayar pemerintah atas pinjaman yang diberikan BI. Pemerintah tidak perlu membayar bunga sama sekali, dan sebagian sangat rendah sekali dibanding bunga pasar yang berlaku.
Esensinya, seperti diumumkan pemerintah, BI ikut mendanai anggaran secara langsung, secara permanen. Karena bunga utang adalah juga utang, dan ketika ia tidak dibayar, secara prinsip porsi utang tersebut diputihkan. Dan, jumlah ini terus bertambah dan terakumulasi setiap tahunnya hingga utang tersebut jatuh tempo. Hal ini sangat mendekati kriteria sebuah debt monetization. Dan sekali lagi ini bukan dugaan apalagi tuduhan, tetapi memang diumumkan apa adanya oleh pemerintah dan BI.
Dan ini menjawab pertanyaan kedua saya di bagian sebelumnya, bahwa ternyata kelanjutannya BI tidak sekedar menalangi, tetapi juga membiayai belanja negara.
Lazimnya, pihak yang berutang memiliki dorongan untuk mengakhiri utangnya karena utang tersebut ada biaya, yaitu bunga. Sebaliknya, ketika utang tidak ada biayanya sama sekali, dalam konteks kebijakan burden sharing ini, dapat membangkitkan “motivasi” untuk melakukan debt monetization dalam skala yang lebih besar.
Misalnya, jika utang tersebut dijadikan perpetual atau quasi perpetual dengan diperpanjang terus menerus atau dengan jangka waktu jatuh tempo yang sangat lama. Toh, tidak ada biaya apa-apa. Jika ini terjadi, telah terjadi debt monetization sesungguhnya. Dalam kata lain, helicopter money ditaburkan oleh BI pada pemerintah.
Perlu juga dipahami, intervensi terhadap BI, melalui skema “burden sharing”, merupakan wujud dari eskalasi pelonggaran disiplin fiskal itu sendiri. Target defisit anggaran yang awalnya sekitar 5% melejit menjadi 6,34% karena tekanan dari sisi pendapatan dan belanja. Hal inilah, yang saya pahami, memicu eskalasi lebih jauh dalam mengintervensi atau mengorbankan independensi BI.
Menakar Risiko Stratejik
Bagi saya, kita telah melewati sebuah tonggak sejarah baru, we crossed the border. Independensi BI dan prinsip pemisahan antara pengelolaan fiskal dan moneter telah berakhir. Mungkin tidak sepenuhnya, mungkin tidak selamanya. Disiplin fiskal berkaitan dengan limit defisit anggaran juga dilintasi. Pertanyannya, apakah ini sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik?
Tentu, akan selalu ada aspek positif dan negatif dari sebuah kebijakan, yang perlu dilihat dari berbagai perspektif.
Dari sisi kebijakan taktis jangka pendek, barangkali banyak argumen untuk mendukung pelonggaran disiplin fiskal dan pengorbanan independensi BI untuk mendanai APBN, seperti yang kita bahas sebelumnya, dan berbagai penjelasan dari pemerintah. Dan, ketika output gap sedemikian besarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai efek inflasi dari kebijakan ini.
 Tapi, perlu diketahui setiap ekspansi moneter yang langsung diterjemahkan dalam belanja sektor riil adalah inflationary. Memang, bisa jadi efeknya tidak signifikan, atau secara absolut tidak “terlihat” karena level inflasi memang sangat rendah saat ini. Setidaknya, ekspansi moneter untuk belanja fiskal mempercepat menuju threshold point yang mentrigger inflasi.
Tapi, perlu diketahui setiap ekspansi moneter yang langsung diterjemahkan dalam belanja sektor riil adalah inflationary. Memang, bisa jadi efeknya tidak signifikan, atau secara absolut tidak “terlihat” karena level inflasi memang sangat rendah saat ini. Setidaknya, ekspansi moneter untuk belanja fiskal mempercepat menuju threshold point yang mentrigger inflasi.
Jadi uang yang “dicetak” oleh BI untuk pemerintah bukanlah uang gratis turun dari langit. Biayanya bisa jadi ditanggung seluruh warga dalam bentuk inflasi, kini atau di masa yang akan datang.
Pertanyaan yang paling krusial adalah, apakah kebijakan yang didesain temporer ini akan menjadi preseden, atau bahkan menjadi rejim kebijakan baru yang lazim. Perubahan UU yang melonggarkan batas 3% defisit anggaran memang tidak berlaku lagi pada tahun 2023. Artinya disiplin fiskal kita kembali seperti biasa pada saat itu.
Jika fiskal kita kembali disiplin seperti biasa, kebutuhan pendanaannya pun kembali normal seperti biasa. Jadi, BI pun tidak perlu “direcoki” pemerintah lagi. BI pun dapat kembali independen sepenuhnya, fokus pada pengelolaan dan kebijakan moneter, tidak harus lagi terlibat dalam pendanaan fiskal negara.
Tapi apakah ada jaminan ini tidak menjadi preseden. Apakah ada jaminan pemerintahan atau parlemen berikutnya tidak menggunakan kebijakan yang sama, mengeluarkan Perpu yang serupa. Bisa jadi dengan alasan bahwa tidak fair bagi mereka mewarisi akibat defisit yang besar dari periode pemerintahan sebelumnya, dan memutuskan “menunda” normalisasi anggaran tersebut. Fiscal deficit is addicting, kata ekonom.
Ada atau tidak ada kebutuhan fiskal yang besar, apakah ada jaminan independensi BI dipulihkan secara permanen dan tidak diganggu gugat. Apakah ada jaminan, intervensi terhadap BI kelak tidak out of control yang membawa risiko klasik, krisis kepercayaan moneter, runaway inflation dan depresiasi mata uang.
Dalam kata lain, moral hazard dapat menunggangi kebijakan yang genuine. Setiap kebijakan dapat dijustifikasi, argumen bisa ditemukan, selama ada kesepakatan politik semuanya bisa terjadi.
Kecenderungan dan wacana serupa di beberapa negara maju, seperti diskusi MMT (Modern Monetary Theory) sebagai perpanjangan dari QE (Quantitative Easing), barangkali memberikan justifikasi tambahan untuk merombak benteng disiplin fiskal dan independensi bank sentral.
Membangun Konsensus Mengenai Kriteria dan Tata Kelola
Rasional terhadap pelonggaran disiplin fiskal dan intervensi terhadap independensi BI telah kita dengar dengan baik dari otoritas, dan kita pahami. Kita perlu mendengar juga komitmen, upaya, strategi, agar ini tidak menjadi preseden, agar tidak menjadi sumber moral hazard. Ini bukan sebuah kebijakan biasa, ini sebuah perubahan yang monumental, yang membawa kita memasuki “unchartered territory” yang tidak sepenuhnya kita tahu bagaimana endingnya.
Keputusan yang diambil pemerintah, apalagi dengan kesepakatan DPR adalah sesuatu yang sah secara hukum dan politik. Namun, sepertinya diperlukan konsensus akademisi dan pakar yang independen untuk membantu membangun kriteria-kriteria dan tata kelola sebagai acuan yang bonafid secara keilmuan. Kita tidak dapat hanya mengandalkan kepada niat baik dari birokrat dan politikus, karena kita tidak tahu siapa pemimpin, birokrat, dan politikus yang akan memegang kekuasaan di masa yang akan datang. Seperti apa visi dan kepentingan mereka.
 Apa kriteria dasar menurut akademisi yang layak untuk mengorbankan disiplin fiskal. Apakah perkiraan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan sekitar 0% seperti sekarang adalah sebuah pain threshold, sehingga sudah layak untuk melonggarkan disiplin fiskal seperti yang tertera dalam UU.
Apa kriteria dasar menurut akademisi yang layak untuk mengorbankan disiplin fiskal. Apakah perkiraan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan sekitar 0% seperti sekarang adalah sebuah pain threshold, sehingga sudah layak untuk melonggarkan disiplin fiskal seperti yang tertera dalam UU.
Apakah harus menunggu pertumbuhan negatif seperti pernah terjadi 20 tahun lalu, atau seperti yang terjadi saat ini di banyak negara lain saat ini, yang rata-rata diperkirakan tumbuh negatif -4% to -5%. Atau ada kriteria-kriteria lain. Mungkin perlu diatur juga berapa limit maksimal baru, karena defisit dan utang itu adalah candu, menurut ekonom.
Apa kriteria dasar yang dapat memicu intervensi terhadap independensi BI untuk memberikan dukungan likuiditas atau real transfer dalam mendanai APBN. Apakah level defisit anggaran, kondisi pasar keuangan seperti tingkat bunga, valuasi pasar, dan lain-lain.
Bagaimana tata kelola yang baik yang harus dibangun untuk menghindari moral hazard, untuk menghindari pelonggaran ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terutama di masa mendatang, ketika pelonggaran disiplin fiskal dan intervensi terhadap independensi BI bisa saja dianggap suatu kewajaran dan memiliki preseden di masa lalu.
Semoga Indonesia bisa melewati krisis pandemi ini dengan baik, pemerintah bisa menavigasi dengan berbagai strategi dan kebijakan yang diperlukan dengan tanpa melupakan untuk mengukur implikasi stratejik jangka panjang. There should be no room for complacency.
* BACA JUGA:
— Ke(tidak)sempurnaan Seorang Pemimpin
— Mitos Sharing Economy dan Perusahaan Teknologi
— Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mata Uang Dalam Jangka Menengah
— Louis Vuitton dan Hermes Hanya Jual Merek?
Salam, RF – www.FrindosOnFinance.com![]()