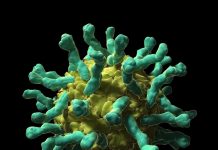2014 – Pada Semak-semak Palak Pisang
“Ya, ini makam putri-putri Maria, ada tiga orang,” ujar cucu Maria ini sambil menunjuk tiga pusara sederhana yang lokasinya hampir berjejeran. “Sebetulnya Maria memiliki empat orang anak perempuan, tapi seorang meninggal pada usia sangat dini. Aku pun tak ingat siapa namanya,” tambahnya.
“Maria seorang wanita cantik pada masa hidupnya ya,” aku sekedar mengulang cerita yang pernah kudengar.
“Nenekku cantik sekali,” sang cucu menimpali dengan bangga, “meski aku tak pernah melihatnya langsung.”
Aku tahu Maria meninggal pada usia muda, belum mencapai empat puluh tahun, meninggalkan tiga putri dan dua orang putranya.
“Kau bilang sebelumnya, bahwa sungai itu tak jauh dari sini?” aku bertanya.
“Betul. Kira-kira seratus meter ke arah bukit sana, dibalik kebun-kebun dan rumah-rumah ini. Bukit yang kau lihat itu, sebetulnya berlokasi di seberang sungai.”
Panas mulai menyengat di tengah pandam pekuburan yang hampir tak berpohon ini. Kami memutuskan untuk kembali saja ke pusat desa, sebelum melanjutkan perjalanan lebih jauh.
Lima menit dari lokasi makam anak-anak Maria tadi, sang cucu memelankan kendaraannya, sambil menurunkan jendela mobil dan menunjuk ke arah kanan jalan.
“Muchtar dimakamkan di sana, persis dekat pohon yang paling besar itu,” ia memberi tahu sambil memberhentikan mobilnya sejenak.
“Makam dengan pagar-paga besi itu kan?”
“Betul sekali.”
“Dan, berapa lama perjalanan menuju pusara Maria?”
“Kira-kira tujuh jam, itu pun aku tak yakin dapat menemukannya,” ujarnya. “Tiga puluh tahun yang lalu, menjelang akhir hidupnya, Muchtar pernah mendatangi lokasi makam Maria. Tapi ia tak menemukannya.”
***
1956 – Pada Sebuah Musim Ketika Hujan Membasahi Tanah.
Kesehatan Maria makin memburuk. Di tengah rintik hujan, hari itu Muchtar kembali menggendong tubuh Maria, membopongnya ke dalam kendaraan. Kendaraan melaju menuju negeri Kerinci. Harapan Muchtar adalah seorang dokter Belanda yang masih bertugas melayani masyarakat Kerinci, walau negeri ini sudah sebelas tahun lepas dari jajahan Belanda.
Di kota kecil yang sejuk itu, Maria menghembuskan nafas terakhir dalam pelukan Muchtar. Muchtar mengikhlaskan kepergian Maria setelah hampir sembilas belas tahun hidup bersama. Muchtar juga mengikhlaskan Maria untuk beristirahat abadi di negeri Kerinci itu, negeri yang terasa jauh kala itu. Titik-titik hujan yang membasahi pusara menyembunyikan tetesan air mata Muchtar, ketika ia melirihkan ucapan selamat tinggal dalam untaian doa dan kata-kata cinta.
1937 – Pada Sebuah Puncak Malam Berpurnama
Sembilan belas tahun sebelumnya, beberapa saat sebelum perang dunia kedua bermulai, sebuah kereta kuda bersiaga di pinggiran sungai sebuah desa. Meski gulita, namun cahaya bulan purnama cukup terang membias di aliran air sungai.
Sekian ratus meter dari situ, sebuah keramaian dan kemeriahan tengah berlangsung. Adalah sebuah tradisi di desa ini, pernikahan berlangsung menjelang tengah malam. Seringkali bisa melewati tengah malam, jika segala macam prosesi, terutama adu pantun berpantun, belum memuaskan kedua belah pihak.
Muchtar, sang pengantin pria, sangat tegang sekali malam itu. Meski saat itu Maria tidak ada di hadapannya, Muchtar tak kuasa menahan kesabaran untuk segera melihat Maria. Fikirannya melayang pada masa-masa ketika ia harus mengakui, bahwa ia bertekuk lutut tak berdaya jatuh cinta tiada terkira pada Maria.
Maria, gadis cantik desa, berkulit bersih dengan rambut panjang hitam terurai. Kelembutan hati dan perilakunya diimbangi dengan kemandiriannya. Maria juga seorang gadis yang cerdas, satu dari sangat sedikit wanita di desa itu yang bisa melanjutkan pendidikan menengah Belanda di kala itu. Tentu, tak sembarang pria yang berani mendekati Maria.
Tapi Maria akhirnya luluh pada Muchtar. Pria muda gagah, tinggi dan tegap, bermata sedikit sipit, dan berhidung mancung. Dan, Muchtar adalah pria yang cerdas berpendidikan. Tak banyak yang meragukan suatu saat Muchtar akan menjadi tokoh di desa ini.
Cinta Maria, cinta Muchtar, cinta Maria dan Muchtar, tumbuh bersemi ketika mereka bertemu di kota kecil sekian ratus kilometer dari desa mereka, ketika mereka mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan. Muchtar bersumpah pada Maria, ia akan membahagiakannya hingga akhir hayatnya. Maria luluh pada tekad dan cinta Muchtar, dan berjanji akan mendampingi Muchtar menghabiskan sisa hidupnya.
Ketika waktu terus beranjak malam, para ninik mamak masih belum tuntas dengan pantun-berpantun mereka, Muchtar makin tegang. Ia makin tak sabar, wajah Maria terus hadir dalam fikirannya.
Dua orang lelaki di atas kereta kuda di pinggir sungai juga semakin tegang, seharusnya mereka tidak menunggu sebegitu lama. Sesekali sang kuda meringkik pelan, sebelum ditepis agar diam.
Persis ketika bulan purnama memuncak diubun-ubun, kedua belah pihak akhirnya bersepakat. Pantun terakhir pun disampaikan sang mamak. Muchtar berdebar. Muchtar bergetar. Pengantin wanita dihadirkan. Mucthar makin gemetar. Ia seperti tidak menjejak di bumi. Jiwanya seperti entah berada dimana. Namun ia dapat menyelesaikan ijab kabul dengan baik.
Orang-orang bergembira, ucapan keceriaan dan tawa bergema, sebelum satu persatu mereka meninggalkan tempat prosesi pernikahan.
“Aku telah memenuhi janji Ayah,” gumam Muchtar. “Tapi maafkan aku Ayah. Dan, sungguh maafkan aku, kau wanita jelita yang baru saja kunikahi…”
Setetes air mata bergulir di pipi Muchtar. Namun tekadnya kuat. Cintanya tak pernah padam. Muchtar menyambar tas kecil yang telah ia persiapkan, hanya dalam sekejap tanpa sepengetahuan siapa pun, Muchtar melompat keluar jendela. Ia lari. Muchtar lari. Muchtar lari sekencang-kencangnya menembus kepekatan malam.
Dua orang lelaki di kereta kuda segera melompat turun ketika melihat bayangan seorang lelaki yang berlari kencang ke arah mereka. Ia adalah Muchtar. Mereka secepat kilat membantu Muchtar naik ke atas kereta kuda. Kuda meringkik memecah keheningan ketika sebuah pecutan kuat menghantam punggungnya, untuk kemudian berlari kencang merambah malam membawa tiga lelaki di atas kereta itu.
Muchtar tak kuasa melepaskan emosinya. Ia sesenggukan menangis mengucurkan airmata. Angin dingin malam berkelebat seiring ketepak kaki kuda yang melesat membelah kegelapan.
***
2014 – Pada Lintasan Rimba Kerinci Seblat
“Ayahnya tidak pernah merestui Muchtar untuk menikah dengan Maria,” ujar sang cucu. “Bahkan ayahnya merasa sangat malu dan marah ketika tahu mereka menjalin hubungan cinta. Sangat tidak pantas pada jaman itu.”
“Ayahnya Muchtar sudah punya jodoh pilihan untuk Muchtar kan,” aku retorik bertanya.
“Betul. Wanita muda cantik, kemenakan sang ayah. Muchtar akan pulang ka bako jika menikahi wanita pilihan ayahnya tersebut. Tentu ini akan disambut luar biasa oleh keluarga besar,” sang cucu Maria ini menjelaskan.
“Tapi, Muchtar tak dapat berpaling lagi dari Maria, nenekku yang cantik dan lembut. Di sisi lain, melawan perintah ayah pada jaman itu sangat sulit dilakukan. Apalagi aku dengar, jika Muchtar tidak mau menikahi kemenakan ayahnya itu, sang ayahnya akan menceraikan ibunya Muchtar, “ tambahnya.
“Intinya, ayahnya tetap meminta Muchtar untuk menikahi kemenakannya. Ayahnya meyakinkan, bahwa wanita pilihannya adalah wanita yang hebat. ‘Begitu kau menikahinya, ijab kabul selesai, kau akan langsung jatuh cinta padanya, dan kau pun sudah memenuhi keinginanku’, begitu kata sang ayah.”
Di antara kekalutan, dan juga ketakutan pada sang ayah dan keluarga besar, dan entah pertimbangan apa lagi, Muchtar menyetujui keinginan sang ayah untuk menikahi wanita pilihan ayahnya. Yang penting aku sudah menikahinya, begitu fikir Muchtar. Begitu selesai ijab kabul, Muchtar merasa kewajiban untuk memenuhi keinginan ayah dan keluarga besar selesai.
Kereta kuda yang berlari di sepanjang sungai malam itu, membawanya lari ke pusat desa. Dan di sana Maria sudah menunggu dengan walinya. Mereka terus lari menjauh, makin jauh. Pada suatu tempat, Muchtar kembali mengucapkan ijab kabul. Kali ini dengan Maria di sampingnya.
“Saya rasa Muchtar telah melakukan perlawanan adat yang cukup besar. Mempermalukan keluarga ayahnya, dan mempermalukan pengantin perempuan pilihan ayah itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana keluarga yang dipermalukan bereaksi,” aku berkomentar.
“Betul sekali, dan wajar sekali mereka marah. Mereka sangat marah tentunya. Tetapi, saya cukup kagum dan mengapresiasi mereka masih mampu mengendalikan amarah, karena tidak ada pertumpahan darah. Karena, sebetulnya, tanpa pernikahan ini pun kami semua bertalian darah. Yang jelas, keluarga Maria terusir dari kampungnya, karena dianggap telah mempermalukan kaum. Muchtar dan Maria pun dikucilkan sekian lama. Bahkan, anak-anak Muchtar dan Maria sering mengalami perlakuan yang sangat tidak menyenangkan selama bertahun-tahun. Butuh dua tiga generasi untuk akhirnya bisa pelan-pelan menyembuhkan luka antar kaum ini, “ cerita cucu Maria dan Muchtar ini.
Setelah hampir tujuh jam, termasuk melewati jalan yang sedemikian parahnya sepanjang perlintasan Taman Nasional Kerinci Seblat, mobil yang kami tumpangi akhirnya pelan-pelan turun menuju lembah Kerinci. Di depan kami terbentang lembah yang hijau dan subur. Sebuah kota kecil berada persis di tengahnya. Di sebelah kiri terlihat Gunung Kerinci yang gagah dari arah Sumatera Barat seperti menjaga kota kecil ini. Ke arah kanan kota menuju Jambi terlihat Danau Kerinci membiru dari atas sini. Negeri yang indah. Sungguh Indah.
***
Kami pasrah, bahwa tidak mungkin lagi menemukan pusara Maria. Lahan dan bukit yang dulu kala adalah pandam pekuburan sudah berganti fungsi menjadi berbagai gedung. Dan, masyarakat sekitar pun sudah hampir tidak ada yang ingat lagi bahwa dulu di situ ada sebuah pemakaman.
Kami memarkirkan mobil di halaman Rumah Sakit, kemudian duduk di bangku panjang bersama wajah-wajah suram penunggu pasien. Pada udara beraroma karbol, kami menghirup nafas-nafas terakhir kenangan cinta Muchtar pada Maria. Di sini Maria menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pelukan Muchtar. Ia masih muda dan cantik waktu itu, dalam usia tiga puluh enam tahun.
“Mungkin kakek Muchtar melakukan sesuatu yang melukai wanita lain, melukai kaum lain. Mungkin. Tapi bagaimana pun, kalau bukan karena cintanya yang besar pada nenek Maria, pada zaman yang demikian sulitnya, kita berdua tidak akan pernah ada, Uda,” cucu Maria ini tersenyum padaku.
“Betul, dik. Cinta yang sedemikian besarnya…” aku merangkul cucu Maria ini, yang juga adik kandungku tersayang.
——— Sungai Penuh, 2014.
Catatan: Tulisan ini adalah prosanisasi dari true story sejarah keluarga saya. Akurasinya berdasarkan cerita lisan yang saya terima dari orang-orang tua. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, saya hanya sekedar berbagi dan menjaga sejarah keluarga.
—-
BACA JUGA
- Melintasi Embun
- Angin Melayang Lewat Jendela Tak Berkaca
- Di Pesisir Malam Angin Beterbangan di Atap-atap Rumah, Bergentayangan di Pucuk-pucuk Kelapa
- * Aku Melayang di Antara Sekumpulan Awan Malam Bermandikan Bintang
Salam, RF – www.FrindosOnFinance.com![]()