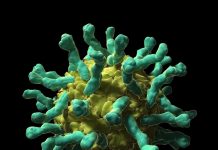“Hai, Ratna…”
Aku menoleh mencari suara di sampingku. Seorang lelaki berdiri tersenyum, sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Sebuah gitar dalam tas hitam tersandang di bahunya. Sambil berusaha membalas tersenyum, aku mencoba mereka-reka lelaki dalam balutan baju hangat berwarna biru tua ini.
“Apa kabar, Ratna?” dia kembali tersenyum. “Hai, baik…” aku menjawab dan mencoba tersenyum juga, sambal berfikir keras siapakah gerangan lelaki dengan kulit sedikit pucat dan berhidung mancung ini. Rambut tipis bertebaran di sebagian wajahnya. Sepertinya dia belum bercukur seminggu terakhir.
“Boleh aku duduk di sini?” tanyanya dengan sopan, sambil tetap tersenyum. Aku rasa wajahnya memang selalu tersenyum. “Ya, tentu saja,” aku berujar sambil menjulurkan dan membuka tangan. Toh, aku hanya sendiri di bangku yang cukup panjang di pinggir promenade ini. Dia tersenyum mengangguk mengisyarakatkan terima kasih, kemudian meletakkan buku yang digenggamnya di atas bangku, dan menyandarkan gitarnya di belakang.
Beberapa helai daun kuning kecoklatan jatuh ditiup angin petang.
“Musim gugur datang terlalu awal tahun ini, “ ujar lelaki itu, “dan, hembusan angin semakin dingin.”
“Ya, lihat, salju semakin banyak membaluri pegunungan di seberang danau ini,” aku tanpa sadar terbawa topik pembicaraannya.
“Hmm…Aku rasa kau rindu negerimu yang hangat, Ratna?”
Aku memalingkan wajah padanya, menatap matanya yang sepertinya juga tersenyum. Sekelebat aku mencoba mengingat-ingat semua lelaki berusia tiga puluh tahunan yang aku kenal di kota kecil ini.
“Maaf kalau aku kurang sopan. Tapi, apakah kita pernah bertemu?”
Dia tertawa kecil, dan membuka topi flat cap biru mudanya dan meletakkannya di atas buku di sampingnya. Seolah-olah memberikan kesempatan padaku untuk melihat wajah dan rambut coklatnya lebih jelas, untuk membantu ingatanku.
“Maaf, apakah kita pernah bertemu?” aku bertanya lagi.
“Tentu saja. Kita pernah bertemu di sebuah film,” jawabnya.
Di sebuah film?
“Maksudmu kita pernah bertemu di sebuah bioskop?”
“Ratna, kita bertemu di sebuah film. Di sini di promenade Danau Jenewa ini.”
Aku memandangnya sambil mengernyit. Wajah tersenyumnya seperti menikmati kebingunganku.
“Ratna, kau pernah memberhentikan aku memetik gitar di sini. Oke, kau tidak menyuruhku berhenti, atau merampas gitarku. Tapi aku tidak mampu untuk tidak berhenti ketika kau lewat petang itu di musim gugur itu. Iya, aku ingat syal cashmere mu berwarna coklat muda. Rambut hitam panjangmu bertebaran diterpa angin dingin. Saat aku melihat wajahmu, aku tiba-tiba yakin bahwa kau adalah bidadari yang jatuh dari langit. Dan aku spontan berdiri berlari mendekatimu. ”
Aku tertawa dan aku tahu aku tidak mampu menyembunyikan rona merah di wajah. Dia juga tertawa, dan meneruskan bercerita.
“Aku selalu ingat dongeng ibu sewaktu kecil, waktu aku bertanya: ‘Ketika aku besar nanti, aku menikah dengan siapa, Ibu?’ Ibu menjawab bahwa seorang bidadari cantik akan jatuh dari langit untukku. Dia bidadari dari negeri timur yang hangat, dengan rambut hitam yang panjang, bibir mungil, dan mata bundar yang indah berbinar.”
Hmm…aku berusaha untuk tidak tersipu, dan mencoba mengingatkan diri untuk tidak terbawa oleh seseorang asing yang mungkin berusaha merayuku. Tapi ceritanya cukup menarik untuk disimak.
“Lalu, aku bertanya pada ibu, kapan bidadari cantik dari negeri timur yang hangat itu datang padaku. Kata ibu, dia akan datang pada sebuah petang di tepian Danau Jenewa. Mungkin karena ibu ingin sekali menyusul ayah pindah ke Montreux. Ibu bilang, bidadari itu hanya akan datang padaku ketika aku mainkan nyanyian indah pada sebuah gitar. Bayangan bidadari yang jatuh dari langit itu terekam kuat dalam imajinasiku, Ratna.”
Angin kembali berhembus. Aku menjentikkan sehelai daun yang jatuh di pangkuanku.
“Aku mulai lupa cerita ibu tentang bidadari yang jatuh dari langit itu ketika beranjak dewasa. Namun, aku perlahan ingat kembali, ketika aku mulai menghabiskan waktu senggang bernyanyi dan bermain gitar di sepanjang promenade ini. Setengah berharap benar-benar ada bidadari yang jatuh dari langit ketika aku bernyanyi. Walau yang lebih aku harapkan adalah kepingan dan lembaran Euro dari turis-turis yang lewat,” dia tertawa cukup keras.
Aku tertawa kecil, tapi merasa sedikit ganjil karena mulai terbawa dan seperti memahami ceritanya.
“Perancis sepertinya akan dituruni hujan,” aku coba mengalihkan pembicaraan, memandang jauh ke seberang danau, memutar kepala ke kanan ke arah desa Evian yang memang dipayungi awan gelap.
“Seseorang di seberang sana mungkin mengatakan bahwa Swiss akan dituruni hujan, “ timpalnya sambil mendongakkan kepala ke atas. Awan di atas kepala kami sebagian memang berubah kelabu.
“Ratna, aku masih ingat, Eldin yang berjalan bersamamu saat itu hampir marah ketika aku berlari menghampirimu dan mengajakmu berkenalan. Ya, aku mengerti, jika aku menjadi Eldin mungkin aku bisa bertindak lebih agresif.”
Aku menatapnya tajam, “Kau mengenal Eldin?”
“Tentu, Ratna…kita bertiga bertemu sore itu.”
“Dimana?”
“Di promenade ini, di sebuah film.”
Suara riak kecil air danau memercik bebatuan. Burung-burung putih beterbangan. Aku diam. Aku bergejolak. Aku bergejolak dalam diam.
“Maafkan aku, Ratna. Kau tahu ‘kan, kita bertiga sempat berteman. Terakhir kita bertemu aku katakan padamu, Eldin adalah pahlawan, ia seorang pahlawan.”
Aku tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk tidak terbawa ceritanya, dan aku tidak mampu mengendalikan emosi, “Kau bilang padaku di stasiun kereta malam itu, Eldin adalah seorang pembunuh. Aku tidak bisa melupakannya!”
“Maafkan aku, Ratna. Suasana penuh ketidakpastian kala itu. Juga, mungkin kau masih ingat, malam itu aku baru saja turun dari kereta dari Vevey. Aku baru saja kehilangan pekerjaan di perusahaan coklat besar itu, surat pemberhentianku masih tergenggan erat di tanganku. Tapi, memang, seharusnya aku tidak bilang Edlin seorang pembunuh. Maafkan aku.”
Aku mencoba menenangkan diri. Sekian lama aku mencoba untuk tidak berfikir tentang Eldin. Terlalu berat untuk memahami dan menerima semua apa yang terjadi.
“Ratna, ketika perang bermulai, kau tahu bahwa Eldin dan aku bingung bagaimana bersikap. Berita dan propaganda menyengat kami ke ulu hati yang paling dalam. Aku mengukur-ukur sejauh mana aku bisa percaya padanya. Aku yakin Eldin melakukan hal yang sama. Dan, aku dan Eldin tidaklah begitu dekat. Oke, aku sudah akui padamu sebelumnya, bahwa keinginanku adalah untuk bisa sering bersamamu, tidak untuk berteman dengan Eldin.”
Suara turis-turis remaja tertawa di sebelah sana, memotret diri bersama patung Charlie Chaplin. Bocah-bocah berlarian di taman bunga di dekatnya. Beberapa lelaki lokal menggulirkan bola-bola baja bermain Pétanque.
“Ketika Eldin memutuskan mengangkat senjata dan pulang ke Sarajevo, aku marah. Aku berkecamuk, Ratna. Sepertinya Eldin telah memutuskan terlibat langsung dalam permusuhan ini, dan berdiri berhadap-hadapan denganku.”
Aku menggelegak, “Apakah kau berpura-pura tidak tahu kalau Sarajevo dikepung, diblokade, dan dibombardir berbulan-bulan. Apakah kau berpura-pura tidak tahu kalau Camil, adik kecilnya yang baru berumur sebelas tahun, terbunuh sniper ketika berlari membawa suplai makanan dari pelabuhan udara? Apakah kau berpura-pura tidak tahu atau kau memang tidak punya hati?”
Aku tidak ingin menangis. Aku sudah memutuskan untuk tidak akan menangis lagi mengenai Eldin. Karena pilihanku hanya dua, tak akan pernah berhenti menangis atau tak akan pernah menangis lagi.
“Ratna, aku mungkin terlalu jahat dalam menilai Eldin. Tapi kondisi ketika itu, dan suasana hatiku waktu itu sungguh berat. Tapi setelah semua berlalu, aku memahami sebagian besar dari lelaki dan wanita di negeri kami tidaklah bermusuhan satu sama lain. Kami bersaudara satu sama lain, ribuan tahun lamanya, bahkan sebelum agama-agama datang mengkotak-kotakkan kami. Sebagian dari kami tidak melakukan apa-apa. Sebagian dari kami hanya membela diri. Bahkan sebagian dari kami mati-matian untuk menghentikan perang. Tapi benar, sebagian dari kami terbakar kebencian yang dikobar-kobarkan. Dan, sedihnya sebagian dari kami adalah pengobar kebencian itu sendiri.”
“Tapi, aku tidak melihat kesedihan sama sekali di wajahmu ketika kita menerima berita kematian Eldin,” aku memandangnya dengan sinis.
“Ratna, waktu itu aku terguncang dan hatiku tercabik.”
“Aku tidak percaya.”
“Maafkan aku, Ratna, mungkin bukan karena Eldin. Tapi hatiku tercabik melihatmu luluh dalam tangisan. Kesedihanmu adalah kepedihanku. Maafkan juga aku karena, jujur saja, aku merasa kepergian Edlin seolah-olah membawamu lebih dekat padaku.”
“Kau sungguh keterlaluan!”
“Karena aku percaya karena kaulah bidadari yang jatuh dari langit Montreux untukku, Ratna.”
Langit makin gelap di atas desa Evian di seberang sana. Angin bertiup berlarian lebih kencang. Riak danau bergulung menjadi gelombang.
“Apakah kau masih ingat aku menangis, saat kau memutuskan untuk kembali ke negeri khatulistiwamu? Aku tidak ingin menangis seperti bocah kecil lagi, seperti tiga tahun sebelumnya ketika aku kehilangan bidadari yang lain untuk selama-lamanya.”
Aku tersentak, dan menatap wajahnya lekat-lekat, “Kau tidak pernah bercerita padaku tentang seseorang bidadari yang lain”. Aku khawatir ekspresiku bernada cemburu.
“Iya, bidadari yang sangat aku cintai sepenuh jiwaku, sepanjang hidupku. Bidadari yang mendendangkan nyanyian pada setiap tidur masa kecilku. Bidadari yang membangun mimpiku untuk menunggu bidadari yang jatuh dari langit Montreux.”
Oh, Tuhan, aku tak pernah tahu.
“Kau tidak pernah bercerita banyak tentang ibumu. Kau tidak pernah bercerita tentang kepergian ibumu. Maafkan aku, aku bersedih untukmu.” Aku menggenggam tangannya. Sebutir airmata bergulir di pipinya.
“Dimana ibumu meninggal?” aku bertanya.
“Di Kravica.”
“Kravica?”
“Iya, tak jauh dari Srebrenica. Ia memutuskan pulang ke Kravica pada saat yang salah. Dua tahun sebelum ribuan etnis muslim Bosnia dibantai pasukan bersenjata Serbia di Srebrenica, Kravica dihancurkan oleh pasukan bersenjata Bosnia. Hanya satu dari etnis Kristen Ortodoks Serbia di desa Kravica yang selamat, dan dia bukan Ibuku. Aku tahu, penderitaan lebih banyak dialami oleh rakyat Bosnia, tapi ibuku terbunuh. Aku kehilangan bidadari yang sangat aku cintai…”
Aku menggenggam tangannya lebih erat, mengusap bahunya. Airmatanya terus bergulir.
“Aku bersedih untukmu…” aku hanya bisa mengulangi kalimat yang sama.
“Ratna, aku tak ingin lagi kehilangan bidadariku. Kau adalah bidadari yang jatuh dari langit Montreux untukku. Jangan pergi ke khatulistiwa. Jangan pergi. Aku mencintaimu.”
Kilat bersabung di seberang sana, air hujan mengguyur desa Evian. Air mata mengguyur wajah Slobodan, ia menangis tersedu di pelukanku.
***
Bagaimanapun, sudah saatnya aku pergi untuk melangkah pulang, meski dadaku masih terasa sesak. Melewati antrian panjang loket tiket film top box office terakhir, aku meninggalkan gedung ini dan melangkah menyusuri trotoar yang semakin hari semakin tidak rata. Udara masih hangat dan cenderung pengap meski malam telah menggantikan senja. Sebuah bajaj melintas menggelegarkan suaranya tepat di depanku.
*** Seri Pujangga: