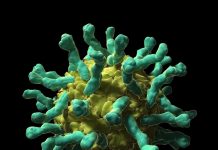Seperempat abad yang lalu saya merasa tidak nyaman, sedikit merasa tersinggung, tersindir sudah pasti. Waktu itu di dalam sebuah laboratorium, bersama dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya saya sedang melaksanakan sebuah praktikum. Menyambung dan memasang kabel-kabel yang berseliweran, dan menyusun beberapa peralatan praktikum. Kemudian, memonitor sinyal-sinyal yang muncul di layar, mengamati, untuk kemudian mencatatnya. Jujur saja, saya tidak menikmatinya sama sekali.
Tapi itu bukan isu yang terlalu besar, yang menjadi masalah bagi saya adalah tulisan di dinding lab: “Sedikit Bicara Banyak Kerja“. Saya merasa tersindir. Saya akui, di lingkungan keluarga atau rekan dekat, saya dianggap banyak omong, kadang ada yang dengan teganya bilang saya gadang ota. Jahat. Jadi tulisan besar-besar dengan huruf kapital dan berwarna merah di dinding laboratorium itu terasa menohok sekali. Barangkali juga karena rekan praktikum saya sebelumnya sempat mengingatkan, supaya saya fokus membantu proses percobaan, jangan ngebacot saja, katanya.
 Saya akui tidak ada yang salah dengan tulisan itu. Peringatan itu pas di tempat seperti laboratorium ini, agar mahasiswa fokus melakukan pekerjaannya. Banyak alat-alat dan bahan yang sensitif, mengkonfigurasi alat-alat percobaan juga dibutuhkan ketelitian. Demikian juga memonitor dan mengumpulkan data percobaan. Lagian ini jurusan Teknik Elektro, bukan Ilmu Komunikasi. Jadi, masalahnya ada pada saya, bukan pada lab ini atau tulisan itu. Saya mungkin sekedar orang yang salah berada di tempat yang salah.
Saya akui tidak ada yang salah dengan tulisan itu. Peringatan itu pas di tempat seperti laboratorium ini, agar mahasiswa fokus melakukan pekerjaannya. Banyak alat-alat dan bahan yang sensitif, mengkonfigurasi alat-alat percobaan juga dibutuhkan ketelitian. Demikian juga memonitor dan mengumpulkan data percobaan. Lagian ini jurusan Teknik Elektro, bukan Ilmu Komunikasi. Jadi, masalahnya ada pada saya, bukan pada lab ini atau tulisan itu. Saya mungkin sekedar orang yang salah berada di tempat yang salah.
Tapi, terlepas dari itu, kita memang dididik mengagung-agungkan kerja, dan menghina-hinakan bicara. Sedikit bicara banyak kerja, begitu propaganda yang sering kita dengar. Itu belum seberapa, ada lagi yang lebih kejam: Tong kosong nyaring bunyinya. Artinya, orang yang banyak bicara itu biasanya bodoh, kira-kira begitu. Sadis sekali. Ada juga yang menakut-nakuti dengan membawa-bawa binatang buas: Mulutmu harimaumu.
“Kita memang dididik mengagung-agungkan kerja, dan menghina-hinakan bicara.”
Sebaliknya, kita didorong untuk tak banyak bicara atau diam. Diam itu emas, katanya. Seolah-olah bicara itu, maaf, tinja. Ungkapan serupa juga kadang kita temukan:Diam-diam ubi berisi, diam besi berkarat. Atau versi yang melankolis: Diam-diam menghanyutkan.
Apa benar diam adalah emas? Saya tidak yakin, kalau Bung Karno diam saja, Bung Hatta manut-manut saja, saya yakin perjalanan bangsa kita akan berbeda. Bahkan, Pak Jokowi yang bersemboyan Kerja, kerja, kerja, terpaksa juga berbicara banyak.
Yang saya khwatirkan adalah kita mendikotomikan antara bicara dan kerja, antara bersuara dan diam. Kita mengadu-domba mangap dan mingkem. Seolah-olah kalau situ bicara berarti situ nggak kerja. Salah. Salah besar. Seringkali bicara adalah bagian dari kerja. Seringkali bicara itu sendiri adalah kerja.
Jika saya kilas balik karir korporasi saya, dan jika ada yang bertanya, apa keterampilan yang saya berharap lebih bagus dari yang saya miliki. Jawaban saya adalah: ngebacot. Saya membayangkan perjalanan karir saya dua puluh tahun lebih itu, akan berjalan lebih lancar jika saya bisa berbicara lebih baik, lebih percaya diri. Kemampuan berbicara, berbahasa, berkomunikasi.
Seringkali saya “kalah” atau mengkeret karena kemampuan berkomunikasi saya kalah dibanding beberapa rekan kerja saya, apalagi mereka yang berasal dari beberapa negara tertentu. Mereka tidak hanya berbicara dengan lancar, penuh percaya diri, dengan kata-kata yang terpilih, tetapi juga dalam rangkaian kalimat yang mengena, dengan intonasi yang pas, serta bahasa tubuh yang meyakinkan.
 Pengalaman-pengalaman seperti ini makin meyakinkan saya betapa pentingnya bicara, atau secara umum komunikasi. Tanpa bicara, tanpa komunikasi, pekerjaan atau karya apapun baru setengah matang. Ide bagus atau produk bagus bertebaran di permukaan bumi ini. Yang kritikal ikut menentukan sukses atau tidaknya ide atau produk yang sama bagusnya itu adalah bagaimana ia dikomunikasikan. Komunikasi tentu saja tidak hanya verbal atau bicara, juga tertulis. Komunikasi tentu tidak hanya berbicara dengan atasan atau rekan kerja, juga dalam diskusi grup, juga dalam presentasi, penulisan laporan, email, komunikasi publik, dan lain-lain.
Pengalaman-pengalaman seperti ini makin meyakinkan saya betapa pentingnya bicara, atau secara umum komunikasi. Tanpa bicara, tanpa komunikasi, pekerjaan atau karya apapun baru setengah matang. Ide bagus atau produk bagus bertebaran di permukaan bumi ini. Yang kritikal ikut menentukan sukses atau tidaknya ide atau produk yang sama bagusnya itu adalah bagaimana ia dikomunikasikan. Komunikasi tentu saja tidak hanya verbal atau bicara, juga tertulis. Komunikasi tentu tidak hanya berbicara dengan atasan atau rekan kerja, juga dalam diskusi grup, juga dalam presentasi, penulisan laporan, email, komunikasi publik, dan lain-lain.
Saya mengerti bahwa pepatah-pepatah seperti ‘tong kosong nyaring bunyinya’ atau ‘diam itu emas’ tersebut ada konteksnya. Namun, ada kecenderungan yang besar dalam masyarakat kita untuk menilai “bicara” itu kurang penting, atau malah cerminan ketidakmampuan. Ini perlu diluruskan dan diseimbangkan. Karena bicara atau komunikasi adalah bagian inheren dari pekerjaan apapun. Bicara itu sendiri adalah kerja.
“As you move up the career ladder, proporsi ngebacot dalam pekerjaan Anda akan makin bertambah dan makin penting”
Bicara adalah sebuah keterampilan, bicara adalah sebuah kecerdasan. Saya tidak melihat kecerdasan berkomunikasi kastanya di bawah kecerdasan matematis, misalnya. Bahkan, semakin tinggi tanggung jawab kita dalam sebuah organisasi, peran komunikasi semakin penting. Dalam kata lain, as you move up the career ladder, proporsi ngebacot dalam pekerjaan Anda akan makin bertambah dan makin penting. Tuntutan dalam kemampuan berkomunikasi makin tinggi. Untuk urusan hitung menghitung, kalkulator atau spreadsheet tersedia, atau seseorang akan mengerjakannya untuk Anda.
 Jadi, mulai hari ini, jika Anda lihat orang yang pintar berbicara, jangan lagi sinis dan bilang: “Itu orang pintarnya bicara doang“. Anda cukup bilang: “Itu orang pintar bicara”. Titik. Kecuali, tentu, jika ia menyalahgunakan kepintaran berbicaranya itu.
Jadi, mulai hari ini, jika Anda lihat orang yang pintar berbicara, jangan lagi sinis dan bilang: “Itu orang pintarnya bicara doang“. Anda cukup bilang: “Itu orang pintar bicara”. Titik. Kecuali, tentu, jika ia menyalahgunakan kepintaran berbicaranya itu.
Dan, mari beramai-ramai kita cari tulisan atau semboyan Tong Kosong Nyaring Bunyinya , kita ganti dengan Tong Berisi Nyaring Bunyinya. Kemudian, Sedikit Bicara Banyak Kerja kita ganti dengan Banyak Bicara Banyak Kerja. Tentu bicara yang benar, dengan cara yang tepat, pada waktu yang pas — jangan ngebacot di laboratorium OK?
Salam, RF – www.FrindosOnFinance.com![]()