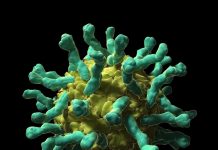“Lha, memang siapa yang jamin Suminah tidak main gila sama laki-laki lain di Singapura?” suara menyakitkan dari Mbak Narti yang ia curi dengar kemarin sore itu masih terus berdenging di telinga Suminah, menusuk jauh ke ulu hati. “Itu saya dengar dari Atun lho,” Mbak Narti menegaskan lagi pada pada beberapa perempuan yang berkumpul di anak tangga rumahnya. Suminah hanya bisa menahan tangis dan amarah, dan diam-diam memutar jalan mengitari belakang rumah Mbak Narti. Beberapa ekor ayam berkotet berterbangan memberi jalan pada Suminah yang melintas bergegas.
“Mbok, Atun itu cuma kerja tiga bulan di Singapura,” ujar Suminah sambil rebah di pelukan ibunya. “Aku ketemu dia sekali tok, di Pasar Geylang, waktu itu ia pinjam uang delapan puluh dollar. Tak lama kemudian, aku dengar ia dipulangkan majikannya ke Indonesia. Aku memang sempat SMS dia beberapa kali minta uangku dibayar. Tapi, aku sudah ikhlaskan uang delapan puluh dollar itu, begitu tahu dia diberhentikan.”
“Sudahlah, Nduk. Lagian bisa jadi Narti salah dengar dari Atun. Sabarkan hatimu,” ujar ibunya sambil mengusap-usap rambut Suminah. “Kita kan perempuan, Nduk,” sambungnya.
Suminah menghela nafas panjang. Sungguh pedih rasanya jika kesetiaannya pada Sodikin dipertanyakan. Dari awal berkenalan di Pasar Bangsri, Suminah sudah jatuh cinta. Sodikin yang tak banyak bicara, namun nampak dewasa dan bertanggung jawab. Suminah selalu merasa nyaman disampingnya. Apalagi setiap berdua dengan Sodikin di angkutan desa, melewati jalan lurus di sepanjang hutan jati yang teduh. Suminah selalu berharap hutan jati itu tak pernah berujung, agar waktunya bersama Sodikin tak pernah berakhir.
Selepas melamar, Sodikin memintanya untuk berhenti bekerja dari pabrik, Sodikin berjanji akan bertanggung jawab atas masa depan mereka.
“Kita kelak akan punya rumah sendiri, Dik,” Sodikin berjanji petang itu.
“Iya, Mas, rumah kita sendiri. Aku sering canggung dengan ibumu dan adik-adikmu”, Suminah menimpali.
“Ibuku sayang padamu, Dik”, ujar Sodikin sambil melirik. Suminah mengangguk sambil tersenyum.
“Keluargaku memang tidak punya sawah, tapi bapak sudah berikan padaku kebun tebu kecil di pinggir sawah itu,” Sodikin menunjuk ke arah timur, Suminah mengikuti dengan pandangan matanya. “Kelak semua tebu itu akan aku tebas, dan aku bangun rumah untukmu dan anak-anak kita,” janji Sodikin sambil memandang Suminah. Bayangan dedaunan terbawa matahari sore jatuh di wajah Suminah yang tersenyum sumringah.
“Alhamdulillah, kamu sudah bisa tersenyum”, suara Ibu menggugah lamunan Suminah. “Jangan terlalu lama menyesali yang sudah terjadi, Nduk.”
“Ndak, Mbok”, ia menjawab pelan. Walau diakuinya, ada perasaan menyesali keberangkatannya ke Singapura.
Suminah ingat Selasa malam waktu itu, Sodikin akhirnya merelakannya pergi. Suminah tak salah, Sodikin memang lelaki pekerja keras penuh tanggung jawab. Namun, dunia tak selalu ramah. Perampingan di pabrik sepatu itu membuatnya kehilangan pekerjaan. Ia mencoba mengadu nasib di industri mebel rumahan, tapi tak banyak yang ia bisa kerjakan, dan beberapa industri mebel juga gulung tikar. Beberapa bulan ini Sodikin hanya sesekali mendapat pekerjaan buruh tani.
“Suminah, pergilah melangkah, terbanglah, seberangilah samudra. Aku akan berdoa pada setiap ayun kakimu,” Sodikin memandang genteng rumah dari kamar kecil mereka.
“Mas, maafkan aku harus meninggalkanmu. Demi masa depan kita, rumah kecil di pinggir sawah, buat anak-anak kita”, Suminah berkaca-kaca.
“Aku yang harus minta maaf padamu, Suminah. Aku sungguh malu, harus membiarkanmu pergi jauh. Tapi segala upaya sudah kucoba, Suminah, segala upaya. Pergilah, mudah-mudahan dunia akhirnya berpihak pada kita. Tapi, jangan terlalu lama karena aku akan merindukanmu.”
Suminah menyeka air mata, airmata membasahi Suminah.
“Kenapa kau menangis lagi, nduk?” Ibu mencoba mengguncang bahu Suminah, “Lupakan Mbak Narti, lupakan apa yang terjadi.”
“Mbok, bagaimana aku harus melupakan semua ini?” Suminah bersuara sedikit keras dan kesal. “Apalagi ucapan ibunya Mas Sodikin kemarin pagi, bagaimana aku dapat melupakannya?”
Suminah hampir tak percaya mendengar kata-kata mertuanya itu. Suminah yakin ibu mertuanya sengaja mengeraskan suaranya dari dapur agar ia dapat mendengar langsung. “Perempuan jaman sekarang suka tidak tahu diri, suami ditinggal lama sendiri, tidak diurus tidak diopeni, masih untung anakku Sodikin sabar hati. Apa dia mau jadi janda?”
Memang, Suminah akhirnya harus tinggal lebih lama di Singapura. Ia tak pernah menyangka kalau delapan bulan pertama ia hanya menerima gaji lima puluh dollar saja, mungkin ia terlalu naif atau memang tidak memahaminya dari awal.
“Gajimu memang 650 dollar. Tapi nggak semuanya buat kamu, majikanmu harus setorkan sebagian untuk pemerintah, levy namanya, 300 dollar sebulan. Nah, kamu juga harus cicil biaya pemberangkatan kamu, biaya pelatihan, biaya asrama. Perusahaan sudah habis duit banyak buat kamu. Kamu cicil sesuai kemampuan kamu saja, 300 dollar sebulan, jadi kamu masih terima 50 dollar,” staf agency itu menjelaskan lagi pada Suminah.
Singapura menang negeri yang indah, namun tak ada kata untuk berleha-leha, Suminah pantang menyerah. Alhamdulillah, pada perasan keringat dan airmata, menetes rejeki yang lama telah didamba. Setiap awal bulan, Suminah melangkah menuju mal tua di sudut Jalan Ochard. “Mas, kukirimkan padamu setiap tetes keringat dan airmata, jagalah senantiasa untuk masa depan kita, rumah kecil di pinggir sawah,” gumam Suminah.
Di hari yang sama setiap malamnya, di sudut sempit paling belakang apartemen majikannya, Suminah menonton pertunjukan terindah di langit-langit kamarnya: Sodikin menebas rumpun-rumpun tebu, menyiangi belukar perdu, menggali pondasi menimbun batu, menyusun bata satu per satu. Pertunjukan di langit-langit kamar ini hanya berhenti ketika Suminah jatuh terlelap dalam senyuman panjang — meski kadangkala berlanjut dalam mimpinya.
“Suminah, aku khawatir padamu, kadang kau tersenyum, kadangkala menangis,” Ibunya memijit-mijit dahi Suminah. “Aku sudah bilang sama kamu, jadi perempuan ya harus sabar, harus ngalah. Kita kan perempuan. Nduk.”
“Kamu masih ingat nasehat Kyai Sobirin tadi pagi?”, tanya ibunya.
Suminah masih merekam kata per kata nasihat Kyai Sobirin tadi pagi.
“Istri yang dijanjikan surga oleh Tuhan adalah istri yang sabar dan tabah, serta melayani dan mengabdi pada suami. Yang senantiasa berkata lembut, menyenangkan hati suami, patuh dan menurut pada keinginan suami. Selalu tersenyum dalam berkata-kata, tampil senantiasa bersih dan wangi, dan tidak tidur membelakangi suami, kentut apalagi. Adalah dosa besar bagi istri yang berani melawan keinginan suami,melukai hati suami, apalagi berkata kasar dan memaki. Jadi tanya pada dirimu sendiri, Suminah, apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu yang sepatutnya sebagai istri?” Kyai Sobirin menghembuskan asap rokok ke luar jendela.
“Tapi Tuhan maha menyayangi”, lanjut Kyai Sobirin, “kamu sekarang masih diberi kesempatan untuk mengabdi pada suami, tunjukkan rasa cinta kamu, bersikap yang pantas sehingga membantu dia bersikap adil. Kelak hanya istri yang bisa menghormati, melayani, dan mengabdi pada suamilah yang mendapat tempat di surga.”
Suminah menghela nafas panjang lagi. “Mbok, sejak kapan ya Pak Sobirin jadi kyai?” Suminah bertanya sambil melepaskan diri dari pelukan ibunya dan tegak berdiri melangkah ke luar kamar.
***
Suminah tak dapat memicingkan mata. Semua peristiwa dalam tiga hari ini di kampung halaman benar-benar melelahkan dan merobek-robeknya.
Berangkat pulang dari Singapura, Suminah menikmati dan mensyukuri setiap detak detik waktu dan setiap derap langkah kaki yang ia ayunkan. Mulai dari menekan tombol lift turun dari apartemen majikannya, perjalanan taksi menuju Bandara Changi Singapura, hingga kecemasan ketika antri di imigrasi bandara di Jakarta. Teman-temannya mengingatkan tentang cerita-cerita yang menakutkan di bandara negeri sendiri.
Ketika mobil angkutan yang membawanya melalui jalanan lurus di hutan jati yang rimbun dan teduh itu, seluruh jiwa dan tubuh Suminah terasa bergetar, bayangan Sodikin terasa begitu dekat. Tapi kali ini ia berharap agar hutan jati ini segera menemukan ujungnya, dan perjalanan menuju desanya segera berakhir.
Gejolak yang sungguh luar biasa mengaduk-aduk perasaan Suminah, ketika ia menjejakkan kaki di ujung jalan desa itu.
Rumah kecil di pinggir sawah, berdinding bata berlantai tanah, angin melayang lewat jendela tak berkaca.
“Mas, inikah istana kita?” senyum Suminah merekah jelita, Suminah serasa terbang tinggi ke angkasa.
“Iya, Suminah. Tapi ada yang belum sempat terkata,” Sodikin menghapus peluh di wajah. “Kini aku tak sendiri di rumah. Engkau pergi begitu lama, begitu lama aku tak kuasa. Maafkan, tapi aku masih mencinta.”
Angin melayang lewat jendela tak berkaca, Suminah terbang tinggi ke angkasa lalu terhempas tak berdaya ke hamparan bumi keras berlapis kaca. Suminah remuk redam pecah berkeping berdarah-darah. Merah.
***
Pagi masih mentah, azan Subuh belum waktunya berkumandang di udara. Ibu Suminah bermandi airmata di bawah pohon cempedak di belakang rumah, meraung memeluk kaki Suminah yang melayang di angkasa.
***
- A tribute to all Indonesian overseas domestic workers.
*** Seri Pujangga:
- Melintasi Embun
- Bidadari yang Jatuh dari Langit Montreux
- Empat Lima Dua Enam
- Di Pesisir Malam Angin Beterbangan di Atap-atap Rumah, Bergentayangan di Pucuk-pucuk Kelapa
- * Aku Melayang di Antara Sekumpulan Awan Malam Bermandikan Bintang
Salam, Riki Frindos – www.FrindosOnFinance.com![]()